6 Bulan Disuruh Kerja Tanpa Digaji, Yusman Menjadi Korban Perbudakan di Kapal Ikan Berbendera China
AKU TAK PERNAH punya pengalaman bekerja di laut, tapi sekali aku menjalaninya pada usia 42 tahun, aku kemudian mengenal kata maut.
Kapal Ikan Berbendera China
Selama 6 bulan 15 hari bekerja sebagai anak buah kapal di Lu Qing Yuan Yu, kapal ikan berbendera China, aku seakan setiap harinya sedang mengkaveling makam di laut lepas. Begitu kata reporter yang menulis kisahku, yang mendatangiku dan kuizinkan mengisahkan pengalamanku.
Pada satu hari gelap bulan Juli 2020, aku dan teman-temanku mesti makan terigu mentah di ruang penyekapan. Pada hari lain, kami harus menyelinap dan mencuri ke dapur jika ingin makan nasi. Sesekali bila kami berhasil mendapatkan dua piring nasi, kami harus membagi rata untuk delapan perut, dengan lauk hanya ditaburi bumbu mi instan.
Dua temanku, Andri Juniansyah dan Reynalfi Sianturi, memilih menyerahkan diri pada kebaikan Tuhan. Mereka meloncat dari kapal Lu Qing Yuan Yu 901 saat melaju di Selat Singapura. Mereka sudah tidak kuat mengalami penderitaan di atas kapal. Aku baca berita kemudian, dan aku bersyukur, mereka diselamatkan nelayan di Kepulauan Riau pada 6 Juni 2020, setelah tujuh jam bertahan di lautan.
Ruang penyekapan kami adalah gudang penyimpanan ikan setinggi hanya satu meter. Ini adalah kapal keempat yang aku naiki, setelah hidupku morat-marit di tiga kapal ikan selama lima bulan. Kapten kapal mengurung kami dari patroli polisi laut.
Terombang-ambing dalam ketidakpastian antara hidup dan mati, aku tidur di tempat berbau anyir yang pekat itu. Aku setiap hari meyakinkan diriku untuk tetap sadar dengan mengingat-ingat keluargaku, rumahku, dan kampung halamanku. Aku tak tahu kapan bisa pulang, apakah aku bisa selamat, apakah aku bisa pulang dan bertemu keluargaku dengan selamat?
Bermula dari Iklan di Facebook
Tak pernah terbersit sedikit pun jika akhirnya aku bekerja mencari ikan di tengah laut.
Selama empat belas tahun, selepas lulus SMA, aku memiliki pekerjaan yang cukup stabil. Aku bekerja sebagai sales untuk perusahaan distributor alumunium dan bahan bangunan. Dari pekerjaan itu aku bisa melanjutkan studi manajemen di STIE Jakarta International College Cempaka Putih. Dari situ aku juga memberanikan diri menata kehidupan rumah tangga dengan menikahi pacarku, Falariyani. Pernikahan kami dikaruniai empat anak.
Pada 2015, aku pindah pekerjaan sebagai konsultan pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia. Diikat kontrak selama tiga tahun, aku memegang satu klien perusahaan, Astra Agro Lestari, sampai awal 2019.
Selepas itu, aku limbung tak keruan.
Beban keluarga meningkat. Cicilan juga. Dan tanggungan-tanggungan lain. Jika semua beban dan tanggungan itu berbentuk bebatuan, barangkali belikatku sudah remuk tak tersisa.
Dengan nyali yang tersisa, aku meminjam modal ke bank, di tengah pekerjaan konsultan yang penghasilannya angin-anginan. Aku dan istriku kemudian melakukan pekerjaan apapun, dari berdagang mendoan, mie ayam, hingga soto. Aku juga sempat berjualan sendok dari pasar ke pasar. Sempat juga menjadi sopir ojek mobil online. Semua itu kulakukan demi menambah penghasilan sehari-hari. Namun, kebutuhan keluarga melebihi penghasilan.
Sampai akhir 2019, aku sempat terpikir untuk mencari pekerjaan di luar negeri, mungkin sebagai buruh migran. Yang kupikirkan saat itu adalah aku bisa mendapatkan penghasilan besar. Aku dan istriku memutuskan untuk menjual mobil demi mencari pekerjaan semacam itu.
Badai nasib yang menimpaku barangkali dimulai dari sini. Mulanya aku berselancar mencari pekerjaan yang mudah menerbangkanku ke luar negeri. Di Facebook, aku menemukan sebuah iklan yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri. Iklan itu menghubungkanku pada seseorang bernama Abdul Aziz, yang mengaku berasal dari Jawa Timur.
Aku mengontak Aziz via WhatsApp. Aziz pandai meyakinkanku. Ia agaknya tahu sedang menghadapi orang yang kalut dan butuh pekerjaan yang mendatangkan uang cepat. Aku berkata aku menginginkan pekerjaan ke luar negeri dalam waktu cepat, tidak mau ribet mengurus dokumen, persyaratan dan lain-lain, tanpa harus mengikuti pelatihan macam-macam.
Ia berkata bisa membantuku. Dalam benakku, aku bakal bekerja di pabrik pengemasan atau onderdil atau pabrik apa saja yang penting gajinya bisa menyelamatkan nasib keluargaku.
Aziz kemudian menyodorkan nomor kontak kenalannya bernama Syafruddin. “Dia biasa memberangkatkan pekerja ke luar negeri,” katanya.
Kantor Imigrasi Tanjung Priok
Aku segera berkomunikasi dengan Syafruddin, juga via WhatsApp. Kami membicarakan persyaratan dokumen. Memintaku menyiapkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah SMA, surat keterangan catatan kepolisian, akta kelahiran, dan foto. Dokumen-dokumen ini diperlukan untuk berkas pendaftaran, katanya.
Ia juga menerangkan apa saja yang perlu dipersiapkan saat mulai bekerja di luar negeri hingga gaji bulanan.
Syafruddin berkata aku bisa bekerja di pabrik atau perusahaan manufaktur, seperti yang kuinginkan. Pekerjaan itu bisa memberiku gaji besar, katanya.
Semakin mantaplah tekadku. Aku bahkan sudah membayangkan bisa bekerja di Korea Selatan, yang dari informasi yang kubaca di internet gajinya sampai Rp21 juta per bulan. Syafruddin mengiyakan saja kemauanku.
Tapi, kemudian, Syafruddin berkata aku perlu menyiapkan Rp55 juta. Alasannya, uang segitu buat mempermudah proses persyaratanku.
Aku kaget. Mencoba menawar. Tapi ia bilang tidak bisa. Aku tetap harus membawa uang sebanyak itu.
Aku baru bertemu langsung Syafruddin saat membuat paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 10 Oktober 2019. Ada banyak orang yang mengurus dokumen di sana. Salah satunya dokumen bernama BST alias basic safety training; sertifikat yang dimiliki seorang pekerja setelah lulus pelatihan dasar-dasar keamanan pekerja. Ada juga yang mengurus Buku Pelaut.
Aku masih ingat detail di tempat itu. Di dalam, ada semacam jalur khusus. Di situ aku difoto dan diwawancarai secara singkat. Prosesnya tak sampai 30 menit.
Nah, aku tidak mengerti kegunaan dokumen-dokumen seperti BST dan Buku Pelaut meski sudah dijelaskan oleh Syafruddin. Ketika berada di kantor imigrasi, aku bertemu Andri Juniansyah dan Dendi, calon pekerja lain yang diurus Syafruddin. Andri berasal dari Sumbawa dan akan menjadi kawan senasib.
Barulah di situ aku mengerti BST itu semacam lisensi untuk melaut bagi ABK, tepat ketika Syafruddin membantuku membuatkan sertifikat BST yang kudapatkan tanpa harus melalui serangkaian pelatihan.
Syafruddin meyakinkanku BST yang kupegang adalah “BST sementara.” “BST yang sebenarnya,” katanya, “belum diterbitkan.”
“BST sementara ini untuk lolos persyaratan agar kamu bisa membuat paspor,” katanya.
Namun, aku merasa mulai ada sesuatu yang ganjil ketika pembuatan BST bersama lima orang lain di kantor imigrasi.
Aku masih meyakini aku bakal dipekerjakan di darat, bukan di laut. Ketika aku sudah mendapatkan BST, aku juga jadi kepikiran saat itu apakah aku tidak akan bekerja di darat?
Aku juga baru mengetahui saat itu Syafruddin bekerja di perusahaan penyalur buruh migran bernama PT Asfiz Langgeng Abadi yang beralamat di Bekasi. Aku tahu ini karena aku bertanya langsung ke Syafruddin.
Dari “uang persiapan” Rp55 juta yang harus aku transfer ke Syafruddin, aku diminta olehnya untuk membayar “uang muka” Rp10 juta setelah proses pengajuan pembuatan paspor di Tanjung Priok. Aku menurutinya. Syafruddin hanya memberiku kuitansi sebagai bukti pembayaran uang muka itu.
Pengurusan paspor dan dokumen lain di kantor imigrasi itu berjalan setengah hari kerja. Tiga hari kemudian, Syafruddin mengabarkan paspor untukku sudah jadi.
Masa Penantian 3 Bulan
Sampai Januari 2020, aku menunggu kabar selanjutnya dari Syafruddin. Di tengah menunggu itu, sekitar Desember 2019, ia menyarankan aku ikut program pemerintah bernama “G to G” dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Aku semakin bingung. Aku justru ditawari peluang dari pihak lain yang sama-sama tujuannya berangkat kerja ke luar negeri. Tapi, kata Syafruddin, ada jatah pemerintah atau kuota untuk orang lain yang sebelumnya sudah bayar kemudian mengundurkan diri.
Dan, kalau aku menerima tawaran itu, menggantikan orang lain tersebut, “kamu harus menambah lagi Rp10 juta sebagai biaya pendaftaran supaya kamu masuk sebagai kandidat dalam program G to G itu,” kata Syafruddin.
Aku tak langsung meresponsnya karena kalaupun aku menerima tawaran itu seharusnya aku tak perlu membayar uang lagi, pikirku saat itu.
Aku tahu BP2MI, tapi aku tidak tahu program “G to G” tersebut. (Ketika aku menceritakan ini ke reporter yang menulis kisahku ini, ia berkata program itu artinya “Government to Government”, salah satu skema BP2MI dalam penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, tetapi tidak memungut biaya calon pekerja; kalaupun ada, hanya sekitar Rp300 ribu sebagai biaya tes.)
Nah, soal tawaran itu, aku emoh menambah “biaya pendaftaran”, lebih memilih menunggu dari apa yang dijanjikan Syafruddin sebelumnya.
Kabar meyakinkan dari Syafaruddin akhirnya datang juga. Pada pertengahan Januari 2020, ia mengantarkanku melakukan pemeriksaan medis untuk mengurus Buku Pelaut. Aku kembali lagi ke Tanjuk Priok.
Lokasi cek medis itu di Klinik Oilia Medical Center. Tak cuma aku, ada juga Andri Juniansyah dan tiga orang lain. Keberangkatan kami diurus Syafruddin. Dan kami mengurus Buku Pelaut di Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok.
***
SAAT ITU AKU sedang berjualan di Pasar Cileungsi, Bogor. Syafruddin mengabarkan besok aku harus berangkat. Aku bahkan sudah dibelikan tiket pesawat Tigerair, keberangkatan pukul 14.00. Anehnya, tujuannya ke Bandara Changi, Singapura; bukan ke Korea Selatan, seperti yang sudah kutunggu-tunggu.
Tapi, Syafruddin lagi-lagi menepis keraguanku. Setelah sampai di Singapura, katanya, bakal dicarikan pesawat yang tujuan penerbangannya ke Korea. “Tapi, kalau pahit-pahitnya tidak dapat, nanti naik kapal laut,” katanya, lagi.
“Paling lama dua minggu sudah bisa menepi di Korea kalau pakai kapal laut,” ia menimpali lagi.
Kabar mendadak itu membuatku gelagapan. Kalau aku berangkat besok, aku mesti meninggalkan bekal bagi istri dan empat anakku. Setidaknya pegangan uang sampai aku menerima gaji pertama.
Bingung, cemas, deg-degan, panik, tak berdaya. Segalanya serba cepat. Segalanya mesti diurus saat itu juga.
Aku dan istriku, Falariyani, akhirnya memutuskan menggadaikan buku kepemilikan motor. Kami pergi ke salah satu perusahaan leasing di Tanjung Priok. Kami diberi pinjaman Rp4 juta.
Di sepanjang perjalanan pulang, kepalaku dipenuhi berbagai bayangan yang aku sendiri tak tahu apakah manis apakah pahit nantinya ketika kutinggalkan istri dan empat anakku saat aku bekerja ke luar negeri.
Aku terbayang anak-anakku. Mungkin anakku bakal menjemputku pulang? Mungkin anakku seketika membuka pintu saat melihatku di depan rumah? Terus terang saja, aku tidak tahu sama sekali.
22 Januari 2020, aku pamit kepada mereka.
Perjalanan Banyak Instruksi
Ada banyak instruksi dari Syafruddin di hari keberangkatan.
Kumpul di Kalibata City, Jakarta Selatan. Ketemu dengan teman-teman yang lain. Diharapkan bawa uang pelunasan pendaftaran.
Semua dokumen (Paspor, Buku Pelaut, BST, hasil cek medis) sudah dipersiapkan di titik kumpul. Jangan bawa banyak pakaian. Tidak perlu membawa koper.
Di sana bakal susah. Agar bisa gampang kabur di bandara.
Lokasi titik kumpul pindah ke Hotel Ellysta Jaya, Jakarta Utara.
Aku tiba di hotel itu. Syafruddin buru-buru menagih uang pelunasan yang disebutnya “biaya pendaftaran”. Aku membayar Rp45 juta via internet banking.
Setelahnya, aku pergi ke Bandara Soekarno-Hatta.
Tiba di Bandara Changi, aku dan pekerja lain dijemput oleh seseorang, lalu diantar menuju 7-Eleven. Ia memberikan daftar nama dan, dugaanku, surat jaminan (Letter of Guarantee) kerja ke seseorang yang lain.
Sosok itu mengarahkan kami memasuki loket administratif seperti sebuah jalur khusus. Dari situ kami sudah tiba ke sebuah speedboat. Saat itu juga perasaan bingung, panik, stres menyergapku. Sebenarnya, aku akan dibawa ke mana? Kalau tujuannya ke Korea, kenapa harus menaiki kapal kecil begini?
Ketika speedboat semakin melaju ke tengah laut, aku melihat Andri Juniansyah mengalami kepanikan yang sama. Lalu, perasaan panik berganti ketakutan. Di tengah laut, yang kusadari kemudian diiringi juga patroli laut Singapura, aku rupanya sedang dibawa mengejar sebuah kapal besar berbendera China.
Kapal itu bernama Lu Qing Yuan Yu 213, kapal penangkap tuna dan cumi.
Hari Demi Hari
Orang yang mengantar kami itu awalnya berlaku baik. Ia mengantar kami ke kamar yang tengah dirapikan, melihat peralatan menangkap ikan, memberi pakaian perlengkapan ABK dan mantel. Ada tujuh ABK asal Indonesia. Aku dan Andri ditempatkan di satu kamar.
Namun, yang aku pikirkan di hari pertama di kapal Lu Qing Yuan Yu 213, aku kelaparan. Andri juga. Aku belum makan dari kemarin. Lambungku sangat perih.
Kami memberi isyarat lapar ke kapten kapal. Di meja dapur, ada banyak makanan lezat. Kami mengira hidangan itu bisa dimakan oleh para ABK. Aku cuma makan roti tawar di hari pertama berada di kapal.
Aku berkenalan dengan Agus, ABK asal Lamongan, yang satu kamar dengan ABK asal China. Agus lebih muda setahun denganku; ia sudah berpengalaman sebagai ABK, terakhir ikut dengan kapal berbendera Taiwan. Ia bisa bahasa Mandarin.
Teman sekamarnya berkata kapal yang kami naiki tengah melaju ke arah Samudra Hindia, ke arah Sri Lanka, bukan ke Korea. Saat itulah angan-anganku yang kian menipis, bahwa aku bisa bekerja di sebuah pabrik di Korea, seketika kandas. Aku lemas sejadi-jadinya.
Hari demi hari sebagai ABK dimulai setelahnya.
Kapten kapal memerintahkanku bekerja sepanjang kapal terus melaju. Mulanya aku disuruh merapikan peralatan dan jaring. Kemudian, mandor memberikan masing-masing alat penangkap ikan ke semua ABK.
Dengan jaring selebar separuh lapangan bola dan bertenaga hidrolik, kami mulai menangkap ikan, dengan pengalamanku yang sangat minim dan harus belajar menggunakannya saat itu juga.
Di hari-hari pertama tak banyak ikan yang berhasil kami tangkap. Tapi, kemudian, kami mulai mendapatkan banyak sekali ikan. Persis saat itulah hari-hari terberat. Beban kerja meningkat. Pernah bahkan 22 jam bekerja nonstop.
Aku terakhir berkomunikasi dengan istriku pada 24 Januari. Aku belum sempat mengabari dengan siapa saja aku berada di kapal saat itu. Pesan berbalas terakhir antara aku dan istriku berhenti sejak pertama kali aku makan di atas kapal.
Momen Lebaran pada Mei 2020, aku berada di atas kapal Lu Qing Yuan Yu 910. Jaringan telepon masih susah. Kapten kapal juga menyita handphone kami setelahnya. Pikiranku melayang pada istri dan anak-anakku. Bagaimana mereka bisa makan? Bagaimana mereka memberitahu ke keluarga dan tetangga soal keadaanku? Bagaimana keadaan keempat anakku merayakan Lebaran tanpa bapaknya?
Keluarga Menggelar Tahlilan
Yusman, suami saya, lupa, lalai atau apa… –saya sendiri nggak tahu–menanyakan ke perusahaan penyalur kerja tentang bagaimana kami menerima gaji.
Saya pun baru menyadarinya setelah dia pergi. Dan dia pergi ke mana? Saya sendiri nggak tahu. Jelas, kami ditipu. Tapi kami baru tahu kami ditipu setelah saya tahu Yusman dibawa ke kapal, bukan dijanjikan bekerja di Korea. Bayangan kami, gaji suami saya akan ditransfer dari dia sendiri ke rekening saya. Seperti kamu biasanya bekerja di darat.
Saya baru tahu setelahnya kalau proses kerja seperti ini ada yang namanya rekening gaji delegasi, yang semestinya diterima oleh saya sebagai istrinya.
Saya sama sekali nggak menerima gaji selama Yusman menghilang. Selama hampir setengah tahun nggak ada kabar. Dan saya harus menghidupi anak-anak.
Saya kembali menjual soto, tahu goreng, mendoan, dan lain-lain. Jualan keliling. Juga jualan online. Pagi-pagi saya harus motoran ke pasar, beli bahan-bahan dagangan. Anak saya yang bungsu masih berumur 2 tahun. Saya berusaha tidak menangis. Kembali ke rumah, langsung memasak, mengerjakan ini-itu.
Apalagi situasinya Covid-19. Terpukul banget. Anak sulung yang SMP harus belajar online, jadilah dia yang mengantar setiap pesanan apabila saya masih memasak. Setiap hari begitu.
Pernah saudara memberi Rp100-200 ribu. Saya terus berharap nanti, bentar lagi, bapaknya anak-anak bakal gajian. Secepatnya mengirim ke rumah.
Setiap hari, saya terus-terusan memandang layar HP. Sebulan. Dua bulan. Tiga bulan. Masih belum ada kiriman uang, nggak ada kabar dari Yusman. Di situ saya berpikir, apakah suami saya masih hidup? Apa sudah mati?
Saya memikirkan kondisi kesehatannya. Suami saya orangnya gampang sakit. Gampang flu. Orang gampang flu kerja di kapal mau jadi apa?
Setiap tengah malam, saya seperti orang gila. Duduk memandang jam. Memandang ke luar rumah. Berharap Yusman memberi kabar. Berharap suami saya muncul di depan rumah. Setiap hari, setiap jam, saya cek HP, siapa tahu suami saya menelepon. Kalau ada panggilan telepon, deg, berharap itu dari suami saya.
Jangan tanya kondisi kesehatan saya. Berat badan saya merosot. Saya sulit tidur nyenyak.
Pikiran saya pusing dengan cicilan rumah, cicilan motor yang BPKB-nya kami gadaikan.
Ada tetangga yang baik hati sampai meminjamkan emas seberat 10 gram untuk kebutuhan saya membayar tagihan rumah.
Saat Bulan Puasa, saya sedih sekali. Biasanya kulkas diisi persediaan makanan berbuka atau sahur, meski nggak banyak. Saya bingung dan sedih ketika anak-anak meminta makanan. Saya langsung mengingat Yusman, mengingat gimana kami biasanya menjalankan ibadah puasa bersama anak-anak.
Anak sulung saya bertanya, Bapak ke mana? Saya nggak bisa jawab selain memendam hati nyeri.
Karena lama nggak ada kabar dari Yusman, keluarganya di Sukabumi sampai mengadakan tahlilan. Tahlilan itu digelar untuk mendoakan agar suami saya segera pulang ke rumah. Bisa menemui keluarganya lagi. Bertemu anak-anak.
Eksploitasi Manusia
Pada 3 Mei 2020, Yusman dan ABK lain mesti pindah kapal ke Lu Qing Yuan Yu 910. Praktik pindah kapal ini dikenal dengan istilah transshipment. Banyak kapal ikan melakukannya terhadap ABK.
Yusman menuturkan ceritanya kepada saya:
Aku dan ABK lain beberapa kali minta dipulangkan ke Indonesia. Saat di kapal ketiga, yakni kapal kolekting, saat kami mengarungi perairan China pada 16 Juli 2020, kami mau dipindahkan lagi ke kapal keempat. Tapi kami menolak karena tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat jaminan kerja.
Lalu seseorang yang mengenalkan diri bernama Wili, mengaku sebagai agen penyalur kerja dari PT Mandiri Tunggal Bahari, menelepon kami. Ia menelepon karena ada salah satu ABK dari perusahaan itu yang disuruh pindah kapal, dan bekerja di kapal keempat sampai November 2020, dengan iming-iming gajinya ditambah 50 dolar AS per bulan.
Kami juga menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing. Dia meminta kami terus bekerja. Tapi kami kurang yakin dia dari KBRI, terlebih meminta kami bertemu di sebuah pelabuhan di Beijing.
ABK asal China juga mengintimidasi kami. “Jika kami tidak mau pindah kapal sampai jam 11 malam,” katanya, “para pekerja lain akan mengeroyok kami.”
Di pagi hari esoknya, aku disodorkan Surat Pernyataan satu halaman. Surat berbahasa Indonesia dan Mandarin ini menyatakan, bila kami ingin pulang, kami dipaksa bersedia didenda 1.000 dolar AS sebagai ganti tiket pesawat dan dianggap melanggar kontrak kerja. Kami juga dipaksa menyatakan surat pernyataan ini dibuat “dengan keadaan sangat sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.”
Dalam kondisi tertekan dan ingin pulang, aku dan ABK yang lain akhirnya menandatanganinya.
Setelah itu, kami dipindahkah ke kapal keempat karena kami dijanjikan bakal diturunkan di Pelabuhan Busan, Korea Selatan.
Kapal keempat itu menuju Busan selama tiga hari. Selama di perjalanan, kami tidak diharuskan bekerja. Sampai di perairan Busan, kapal sempat berhenti sekitar 4 jam. Tapi, kemudian, melaju lagi ke Korea Utara.
Kami semakin khawatir. Kami memprotes. Tapi, kata kapten kapal, kami tidak jadi diturunkan karena “tidak ada kapal yang menjemput dari Pelabuhan Busan.”
Kami nekat menelepon Kepolisian Korsel untuk minta disambungkan ke KBRI. Namun, karena itu hari Minggu, saluran telepon tidak tersambung. Alhasil, kami pasrah saja.
Selama masa tergelap itu–aku mengira aku bakal mati, putus asa dan panik–kami menolak bekerja karena sudah dijanjikan boleh pulang. Kami juga tidak mau dibagi ke beberapa kapal.
Di kapal itu, kami 8 ABK dari Indonesia tidak diberi makan. Untuk tidur pun, di geladak terbuka selama beberapa malam, kami hanya menggelar alas tipis dan mantel. Setelah itu, kami dipindahkan ke gudang penyimpanan ikan setinggi satu meter. Di tempat itulah kami makan terigu mentah untuk bertahan hidup.
Menginjak hari ke-18 di kapal keempat, pada 3 Agustus 2020, kapal kembali ke China melewati Busan. Aku dan ABK lain meminta sambungan telepon ke Indonesia, meski akhirnya tidak diberi izin.
Kami didorong keluar ruang kemudi. Belum sampai ke laut China, kapal kembali ke Korut melewati Busan, lagi-lagi tidak berhenti. Kami lalu menelepon Kepolisian Korsel untuk minta bantuan, agar bisa keluar dari kapal dan minta disambungkan ke KBRI di Seoul.
Saat itulah kapal keempat yang kami tumpangi dikejar kapal patroli.
Ketika itu, salah satu temanku melambaikan tangan ke kapal patroli, tapi ketahuan mandor China. Akhirnya kami disuruh masuk ke dalam gudang. Kami tidak boleh kelihatan dari kapal patroli tersebut.
Dari dalam gudang, aku mendengar sirine peringatan dan panggilan dari pengeras suara. Tidak lama, kapal berhenti. Polisi patroli naik menggeledah kapal. Aku beserta ABK lain disuruh keluar dari gudang.
Di situ kami diinterogasi. Lalu disambungkan telepon ke KBRI. Lalu kapal kami dikawal kapal patroli dan kapal polisi ke Pelabuhan Ulsan.
Di Ulsan, kami turun. Setelahnya kami satu-satu dicek kesehatannya, dan dikarantina di pelabuhan. Ketika sudah memasuki malam hari, aku dan teman-teman dimintai keterangan oleh pegawai KBRI.
Aku terus mengingat tanggalnya. Tanggal akhirnya aku bisa menginjak kaki ke daratan: 6 Agustus 2020.
Kepulangan Penuh Haru
Aku tak kuasa membendung kebahagiaanku pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020, saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Aku langsung sujud syukur.
Setelahnya, aku dan teman-teman lain dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Aku bertemu istri dan anak-anakku di sana. Kebahagiaanku langsung pecah.
Sesudahnya, aku dan yang lain dibawa menginap di Hotel Marrakesh Inn, Tanah Abang, selama tiga hari. Istri dan anak-anakku menginap pada malam pertama. Pada malam kedua, aku dan teman-teman ABK lain menjalani proses pemeriksaan polisi di kamar hotel.
Kemudian, kami ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Center di Bambu Apus. Aku mengira hanya beberapa hari, ternyata sebulan. Aku diberi upaya pemulihan sekaligus pengarahan untuk bantuan advokasi kasus yang kami alami. Lalu aku diizinkan pulang.
Tentu kamu tahu bagaimana rasanya bisa kembali pulang ke rumah, bertemu istri dan anak-anakku, setelah meninggalkan mereka tanpa kabar selama 6 bulan 15 hari.
Epilog
Aku tahu aku menyesal. Apalagi aku harus kehilangan Rp55 juta, yang seharusnya bisa untuk modal kerja aku dan istriku.
Aku sudah menceritakan semuanya. Terserah kamu mau menilai kesalahanku (atau kesialanku?).
Reporter yang menemuiku menyebut kasusku sebagai “anomali.” Ia bilang jarang ada ABK dengan pendidikan sarjana sepertiku, gampang tergiur pada janji manis dari jaringan perdagangan orang dan perbudakan manusia di laut lepas.
Kata dia, kebanyakan korbannya adalah anak-anak muda yang ingin membantu kesulitan keluarga. Ingin memperbaiki rumah orangtuanya dan sebagainya.
Ia juga berkata kisahku menambah catatan panjang kasus perbudakan modern di laut lepas. Setiap tahun ada saja kabar ABK yang mati di atas kapal, meninggal karena sakit, mengalami kekerasan, dipaksa makan dan minum seadanya, dan dipaksa bekerja berjam-jam. Apakah aku termasuk yang beruntung?
Selama bekerja di atas kapal, aku baru menerima gaji Rp5,6 juta. Aku dan istriku kini menuntut hak pengembalian uang ke Syafruddin sebagai agen yang telah menipuku.
Kini Syafruddin dipenjara karena kasusku. Kasus tindak pidana perdagangan orang. Ia dipenjara bersama Karyanto dan Muhammad Hasbar Yasir alias Daeng. Mereka dari PT Duta Putra Group, perusahaan penyalur awak kapal, yang mengeluarkan surat penerbangan pada 24 Januari 2020. Aku dan enam orang lain disebut kru mereka.
Tanggal itu adalah hari keberangkatanku ke Singapura. Hari itu aku tidak menyadari telah dijual ke kapal China, Lu Qing Yuan Yu.
Aku dan beberapa ABK lain, termasuk Andri Juniansyah dan Reynalfi Sianturi, masih saling berkabar. Kami punya grup WhatsApp. Kesedihan yang sama, penderitaan yang sama di atas kapal, telah menguatkan pertemanan kami.
Kini aku bekerja menjadi sopir teknisi tower. Aku menerima upah Rp100 ribu per hari. Kami tetap banting tulang. Anak-anak harus makan. Anak-anak harus sekolah. Cicilan rumah. Tanggungan kebutuhan yang lain. Semuanya harus pakai uang. Aku dan istriku kembali ke kondisi di awal, hanya saja suaminya pernah menjadi ABK, yang kisahnya telah kuizinkan ditulis oleh reporter yang menemuiku.
Aku juga menyampaikan ke dia, reporter tersebut: Memang kita bukan siapa-siapa, kita hanya ingin mencari keadilan.*
Rute Perjalanan Yusman
Editor: Fahri Salam
Laporan ini adalah serial #PerbudakanABK yang didukung oleh Greenpeace Indonesia
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.
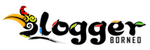





Comments are closed.