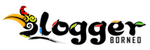BloggerBorneo.com – Dalam era digital yang serba cepat, masyarakat memiliki akses luar biasa terhadap informasi dan juga ruang untuk menyuarakan pendapatnya.
Mengutip dari inca berita, salah satu fenomena sosial yang saat sedang berkembang sebagai salah satu dampak dari kemajuan teknologi ini adalah Cancel Culture atau budaya pembatalan.
Fenomena ini terjadi ketika publik secara kolektif memboikot atau menarik dukungan dari seseorang, kelompok, atau institusi akibat tindakan atau pernyataan yang dianggap tidak etis, ofensif, atau menyimpang dari nilai-nilai sosial yang berlaku.
Asal Usul dan Perkembangan Cancel Culture
Cancel Culture mulai populer di platform media sosial, terutama Twitter, pada awal tahun 2010-an. Awalnya, budaya ini muncul sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban publik terhadap perilaku bermasalah—misalnya, tindakan rasisme, pelecehan seksual, atau diskriminasi.
Dalam banyak kasus, orang-orang yang sebelumnya memiliki kekuasaan atau pengaruh besar, akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari perilaku mereka.
Namun, seiring berkembangnya waktu, Cancel Culture menjadi fenomena yang semakin kompleks. Tidak sedikit kasus di mana seseorang dibatalkan atau ‘cancelled’ bukan karena pelanggaran berat, melainkan karena kesalahan di masa lalu, pernyataan yang ditafsirkan secara salah, atau bahkan karena perbedaan opini.
Tujuan di Balik Cancel Culture
Di balik semangat Cancel Culture terdapat keinginan untuk menegakkan keadilan sosial. Masyarakat ingin memastikan bahwa perilaku yang merugikan orang lain tidak ditoleransi, terutama jika dilakukan oleh orang-orang berpengaruh yang memiliki jutaan pengikut.
Dalam konteks ini, Cancel Culture dianggap sebagai bentuk akuntabilitas publik yang selama ini sulit dicapai melalui sistem hukum atau institusi resmi.
Misalnya, gerakan #MeToo yang mengungkap banyak kasus pelecehan seksual, berhasil “membatalkan” sejumlah tokoh besar yang sebelumnya tidak tersentuh hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa publik memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan, terutama dalam dunia yang semakin terbuka dan terhubung.
Sisi Gelap Cancel Culture
Meski niat awalnya baik, Cancel Culture tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai bahwa fenomena ini sering kali berubah menjadi bentuk pengadilan massa digital yang tidak adil.
Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, reputasi, atau bahkan keselamatan diri hanya karena satu kesalahan yang disorot media sosial, tanpa adanya proses klarifikasi atau hak membela diri.
Tak jarang, netizen dengan mudah menghakimi berdasarkan potongan video, tangkapan layar, atau kutipan tanpa konteks. Dalam kondisi seperti ini, Cancel Culture berubah dari alat perubahan menjadi bentuk perundungan digital (cyberbullying).
Lebih dari itu, efek psikologis dari pembatalan publik bisa sangat berat. Mereka yang menjadi sasaran Cancel Culture sering mengalami depresi, kecemasan, atau bahkan trauma akibat tekanan dan kebencian yang diterima.
Dalam beberapa kasus ekstrem, ada korban yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dengan beban sosial yang ditimbulkan.
Cancel Culture di Indonesia
Di Indonesia, Cancel Culture juga telah menunjukkan eksistensinya. Selebriti, politisi, influencer, hingga brand lokal pernah menjadi sasaran pembatalan akibat pernyataan atau tindakan yang dianggap menyakiti publik.
Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat aktif di media sosial, fenomena ini bisa menyebar sangat cepat dan berdampak luas. Salah satu contoh nyata adalah pembatalan terhadap figur publik yang mengucapkan pernyataan intoleran.
Meskipun beberapa orang kemudian meminta maaf secara terbuka, masyarakat tetap menunjukkan penolakan terhadap mereka dengan menghapus dukungan, membatalkan langganan, atau melayangkan kritik terus-menerus.
Perlukah Cancel Culture Dihapus?
Pertanyaannya, apakah Cancel Culture perlu dihentikan sepenuhnya? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Di satu sisi, masyarakat memang perlu ruang untuk menyuarakan ketidakadilan dan meminta pertanggungjawaban terhadap perilaku menyimpang.
Namun di sisi lain, publik juga perlu menyadari bahwa setiap individu berhak untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kesempatan kedua.
Apa yang lebih dibutuhkan adalah keseimbangan antara keadilan dan empati. Sebelum menghakimi atau membatalkan seseorang, ada baiknya publik mencari klarifikasi, mempertimbangkan konteks, dan membuka ruang diskusi.
Budaya cancel bisa digantikan dengan budaya accountability yang sehat, di mana tanggung jawab diutamakan, tetapi tanpa mengabaikan proses belajar dan perubahan.
Penutup: Mengubah Cancel Culture Menjadi Call-Out Culture
Daripada sepenuhnya “membatalkan” seseorang, konsep Call-Out Culture bisa menjadi alternatif yang lebih membangun. Dalam Call-Out Culture, kesalahan tetap dikritisi, namun dengan cara yang lebih dialogis, edukatif, dan memberi ruang untuk pertobatan serta pertumbuhan.
Kita sebagai masyarakat digital perlu mendorong lingkungan yang adil namun juga penuh kasih. Karena pada akhirnya, setiap orang bisa membuat kesalahan. Yang membedakan adalah bagaimana mereka belajar dan bangkit kembali dari kesalahan tersebut. (DW)