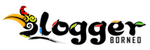Ketika Aditya, anak saya, masih batita, sudah jelas tampak bahwa ia kidal. Saya selalu sigap melindunginya dari orang-orang yang mengatakan “pakai tangan manisnya dong”, ketika secara otomatis Adit mengulurkan tangan kirinya untuk menerima sesuatu dari mereka.
Secepat kilat saya katakan “Adit kidal!” Memaksanya menggunakan tangan kanannya bisa mengakibatkan berbagai masalah mental dan emosional, juga hambatan belajar.
Hal ini saya selalu jelaskan kepada guru-gurunya sejak ia masih TK. Saya wanti-wanti pada mereka, tolong, Adit jangan dipaksa menggunakan tangan kanannya. Ia kidal. Titik.
Stephen Suleeman, pendeta pembela LGBTIQ+, yang meninggal 8 November baru-baru ini tidak seberuntung Adit.
Meski slogan Indonesia adalah “Bhinneka Tunggal Ika”, menjadi minoritas di negeri ini tidak selalu mudah. Namun rupanya selain statusnya sebagai double minority – Tionghoa dan Kristen-Protestan – ternyata Stephen juga kidal, yang membuatnya menyandang status triple minority.
Saya mengenal Stephen secara akrab, tapi saya baru tahu mengenai kekidalannya dari wawancaranya di Theovlogy Channel tgl 5 Des. 2019. Di situ Stephen bercerita bagaimana ia dulu dipaksa menggunakan tangan kanannya oleh guru dan omanya.
Akibatnya ia mengalami trauma dan gagap yang sangat parah. Baru waktu di SD, ia disadarkan seorang temannya bahwa ia kidal, maka ia mulai mengubah cara makannya, menulis, mengerjakan ini-itu, dengan tangan kirinya.
Pelan-pelan, gagapnya hilang, tapi baru benar-benar bisa bicara normal pada usia sekitar 24-25. Bayangkan!
Namun justru trauma kekidalannya inilah yang membawa hikmah bagi komunitas LGBT karena bisa membuatnya berempati kepada LGBTIQ+.
Stephen kidal memang “dari sononya” – LGBTIQ+ juga demikian. Dia bisa merasakan, bagaimana jika LGBTIQ+ dipaksa menjadi hetero, sama trauma dan kacaunya secara mental-emosional seperti ketika dia dipaksa menggunakan tangan kanannya.
20 tahunan Stephen baru bisa sembuh dari traumanya, dan kembali kepada kodratnya sebagai orang kidal, yang bagi dia adalah normal.
Orientasi gender dan seksual LGBTIQ+ juga adalah kodrat mereka, dan normal bagi mereka, seperti halnya cisgender-heteroseksualitas itu normal bagi orang yang kodratnya bukan LGBTIQ+.
Dan tau tidak, ada persamaan antara orang-orang kidal dan kalangan LGBTIQ+: masing-masing merupakan 10 persen dari penduduk dunia!
Meski menurutnya, dia tidak sampai di-bully, tapi di kalangan gereja Stephen terkadang diboikot akibat aktivisme dan advokasinya yang gigih dan amat terbuka terhadap LGBTIQ+.
Namun ia tidak peduli. Seperti yang dikatakannya kepada pewawancaranya, mengkritisi judul acara tersebut yaitu “Deviant Ministry: Finding God in the Wrong Place” (Pelayanan Menyimpang: Menemukan Tuhan di Tempat yang Salah), justru ia mengatakan, ia menemukan Tuhan di tempat yang benar.
Membela LGBTIQ+ itu diyakini sesuai dengan ajaran Yesus Kristus yang menurutnya – jika masih hidup – juga akan membela LGBTIQ+ seperti halnya ia membela yang papa, miskin, sakit, difabel, dan kalangan termarjinal lainnya pada zamannya.
Sebagai seorang muslim, saya yakin jika hidup di zaman sekarang, Nabi Muhammad pun akan membela LGBTIQ+.
LGBTIQ+ dosa? Lha memang orang hetero tidak ada dosanya? Kita semua makhluk berdosa kok! Demikian argumentasi Stephen. Seperti kata Yesus , “Let him that is among you without sin, cast the first stone” (Biarkan dia yang ada di antara kamu tanpa dosa, melemparkan batu yang pertama). Mentang-mentang mayoritas, jangan suka munafik dan benar sendiri ah! Demikian kira-kira Stephen.
Ketika pada bulan November 2019 saya mendapat undangan untuk menghadiri konferensi internasional “Identitas Queer dalam Agama dan Budaya” tentang seksualitas manusia dan teologi queer yang diprakarsai Stephen, saya tercengang.
Luar biasa ini orang, saya pikir, apa tidak takut? Saya mengetahui banyak acara berkaitan dengan LGBTIQ+ yang digrebeg ketika tengah berlangsung, atau bahkan dari awal tidak mendapat izin.
Tapi konferensi tersebut diadakan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta (STFT), jadi mestinya sudah mendapat izin secara sah.
Yang diundang dari mana-mana, selain narasumber dari dalam dan luar negeri, pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia, banyak yang muda pula, dari berbagai agama, bukan hanya Kristen. Wow, betul-betul gambaran pluralisme Indonesia yang sesungguhnya!
Lagi-lagi saya dibuat tercengang oleh Stephen ketika suatu ketika kami chatting lama di WhatsApp mengenai teologi feminis.
Saya kebetulan menemukan sebuah video berjudul “Why Did The Gospels Try To Erase Mary Magdalene?” (Mengapa Injil Berusaha Menghapus Maria Magdalena) yang membahas kontroversi seputar sosok Maria Magdalena.
Saya kirim ke Stephen, bagaimana menurut Anda, saya tanya?
Pandangan umum yang salah mengenai Maria Magdalena adalah bahwa ia seorang pelacur yang bertobat, dan menjadi pengikut Yesus. Yang sebenarnya adalah ia salah satu rasul Yesus, juga seorang saudagar kaya yang mendukung kegiatan Yesus.
Ia yang menyaksikan Yesus disalib, menunggu hingga diturunkan dari salib dan yang membersihkan tubuhnya yang penuh luka dan berlumuran darah.
Tetapi yang lebih krusial lagi adalah bahwa Maria Magdalenalah yang pertama kali menjadi saksi kebangkitan Yesus yang menjadi dasar agama Kristen. Tanpa kesaksian Maria Magdalena, konon agama Kristen tidak akan lahir.
Saya menanyakan Stephen mengenai hal ini.
Tidak saya duga, pertanyaan saya memancingnya untuk mengirim banyak bahan mengenai interpretasi feminis dari sejarah Injil, juga hal-hal yang sengaja dihapus, disembunyikan, atau diputarbalikkan faktanya, seperti yang dilakukan pada representasi Maria Magdalena.
Misrepresentasi ini bukan hanya terjadi dalam agama Kristen, tapi juga Islam dan kemungkinan agama dan budaya lainnya.
Agama Kristen maupun Islam tidak lahir sebagai agama yang menindas atau menomor duakan perempuan, tapi paham patriarki akhirnya yang membuatnya demikian.
Saya lagi-lagi tercengang melihat bagaimana progresif, berani dan bahkan bisa dikatakan revolusionernya teman saya Stephen Suleeman ini.
Ya memang, ternyata selain pembela LGBTIQ+, ia juga seorang feminis sejati. Sikapnya ini ia ingin tuangkan secara nyata dengan melamar menjadi komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024.
Ia meminta saya menulis surat rekomendasi baginya untuk tujuannya ini. Saya merasa sangat tersanjung: Stephen yang begitu saya hormati dan kagumi, meminta saya menulis surat rekomendasi baginya.
Saya melakukannya dengan senang hati dan bangga. Jika ia begitu committed dan berdedikasi terhadap LGBTIQ+, pasti dalam membela perempuan juga ia akan sama. Kaum feminis sangat membutuhkan sekutu laki-laki seperti Stephen, yang tidak diragukan lagi integritasnya.
Sayangnya, ia tidak diterima. Mungkin karena banyak saingan – kandidat lain yang sudah sejak lama berkiprah di bidang hak-hak perempuan.
Secara fisik Stephen memang sudah tidak ada lagi di antara kita akibat sakit ginjal yang lama dideritanya.
Tapi spiritnya untuk membela yang lemah, yang terpinggirkan, untuk melawan kepicikan dan kebencian, serta arogansi yang bersarang dalam patriarki agama dan budaya, akan tetap hidup di dalam hati kita semua yang tersentuh oleh semangat dan kasihnya.
Betapa kehilangannya komunitas LGBTIQ+, sahabat dan keluarga Stephen, tapi menurut saya, juga kehilangan untuk negeri ini. Sesungguhnya, ia mempersonifikasikan apa yang seharusnya menjadi Indonesia. Stephen adalah yang terbaik dari apa seharusnya Indonesia itu.
Julia Suryakusuma adalah seorang penulis, peneliti, aktivis, dan feminis. Ia menulis kolom di The Jakarta Post selama 15 tahun dan menulis buku, di antaranya Julia’s Jihad dan State Ibuism.
Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.![]()