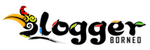Isu Perempuan dan Maraknya Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat
Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia, karena telah mengolah kurang lebih 33 juta ton sawit di tahun 2016. Perkebunan kelapa sawit juga menyokong perekonomian 1,46 juta rumah tangga, dan berkontribusi terhadap mata pencaharian jutaan rakyat Indonesia.
Saat ini, pemerintah memiliki kebijakan yang bertujuan merevitalisasi perkebunan kelapa sawit berskala kecil dengan cara meningkatkan efisiensi produsen kecil, mengurangi kesenjangan produktivitas antara produsen skala kecil dan skala besar termasuk perkebunan, termasuk meningkatkan pendapatan petani, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan.
Hal ini berhasil menarik perhatian para ilmuwan yang tengah terfokus pada efek sosial pertanian perkebunan. Termasuk isu jender di perkebunan kelapa sawit tentang peran penting perempuan sebagai pekerja perkebunan, petani-petani kecil dan anggota integral masyarakat setempat.
Untuk menjelaskan masalah ini, para ilmuwan dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) menginvestigasi dampak sosial sawit di Meliau sebagai bagian inisiatif lebih besar CIFOR untuk memahami dimensi jender ekspansi sawit di Kalimantan.
ISU PEREMPUAN DI KALIMANTAN BARAT
Salah satu contoh kisah sawit di wilayah tersebut adalah Ibu Lila (nama asli diganti untuk melindungi identitasnya). Setiap hari Ibu Lila naik turun bukit di antara barisan sawit, membawa 18 kilogram pupuk dalam keranjang yang diselendangkan di bahunya. Ia akan dibayar Rp 35.000, jika Ia memenuhi kuota dengan menebar 350 kilogram pupuk di sekitar 175 sawit. “Seringkali ketika mengangkut pupuk itu, saya merasa tidak kuat lagi melakukannya, saya lelah sekali,” kata Lila. “Saya pusing ketika menghirup baunya, mata bengkak, saya menangis sampai malam.”
Ini pekerjaan yang mematahkan pinggang, tetapi Lila merasa seakan tidak ada jalan keluar, karena kerja di perkebunan adalah satu-satunya kesempatan agar anaknya tetap bersekolah di SMA. Ibu Lila tinggal di kampung kecil di tengah perkebunan kelapa sawit di Meliau, Kalimantan Barat, Indonesia – lahan yang sejak tahun 1980 telah dikembangkan untuk sawit secara ekstensif.
Ia pun bukan satu-satunya kisah sawit di wilayah tersebut. Keluarga petani kecil mandiri juga mengembangkan tanaman itu. Jika mereka memiliki cukup lahan, serta menanam tanaman sampingan seperti padi dan karet, sawit dapat membantu mereka untuk lebih sejahtera lagi.
KISAH DUA MODEL
Separuh dari total wilayah yang ditanami sawit di Indonesia dipelihara oleh petani kecil. Menurut riset, sawit menawarkan kemakmuran dan pemberdayaan bagi perempuan dan laki-laki, dengan sejumlah lahan tertentu dan dukungan dari pemerintah.
“Di sebagian besar Indonesia, tingkat kemitraan suami-istri sangat tinggi. Mereka bekerja bersama untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jika Anda memberi akses yang cukup bagi mereka untuk mengelola tanaman, mereka akan melakukannya dengan baik,” kata Tania Li, penulis laporan, ahli antropologi dari Universitas Toronto.
Namun sayangnya, tidak semua petani kecil punya cukup akses. Ada dua model di Kalimantan yaitu petani mandiri dan petani kecil yang dibantu oleh ikatan kontrak dengan perusahaan perkebunan besar untuk mengelola perkebunan inti dan pabrik.
Di Meliau, perusahaan swasta memberikan setiap pasangan berupa lahan dua hektar dan mewajibkan mereka menanam sawit. “Lahan sawit dua hektar itu tidak cukup untuk hidup, dan mereka sulit mempertahankannya,” kata Li. “Namun, petani mandiri yang bisa meragamkan sawit dengan sistem pertanian campuran karet dan beras akan lebih aman.” jelas Li.
PEREMPUAN TAK BERLAHAN PALING TERPUKUL
Pada awal 1980, ketika perusahaan minyak sawit pertama pemerintah dibangun di Meliau, pasangan suami istri dari Jawa berdatangan menagih janji pekerjaan tetap dengan gaji yang cukup, rumah gratis, makanan ransum dan perawatan kesehatan. Kondisi ini hanya bertahan satu generasi dan terus menurun. Perusahaan mengurangi jumlah pekerja tetap dan makin menggantungkan diri pada pekerja “kasual”, yang tidak punya pilihan, kecuali bekerja dalam kondisi berbahaya dan tidak aman.
Li meyakini, tren ini tidak hanya khas Meliau, tetapi juga merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari model perkebunan. “Perusahaan dalam wilayah penelitian ini, sebelumnya telah merekrut pasangan, kini mereka hanya membayar lelaki migran sebagai pemetik dan etnik lokal dayak. Perempuan Melayu tak memiliki lahan, akan menjalankan tugas perawatan. Perempuan yang tak punya kebun seperti Ibu Lila berdiri sebagai pihak paling dirugikan dalam sistem ini,” kata Li.
WAKTUNYA MEMIKIRKAN JENDER
Li berpendapat, “Untuk mengurangi ancaman sosial, diperlukan regulasi lebih kuat agar dapat melindungi pekerja perempuan,” Ia juga merekomendasikan pemerintah untuk mengkaji skema petani kecil yang ada, dan merancang program baru guna mendukung petani kecil mandiri.
Peneliti CIFOR, Bimbika Sijapati Basnett berpendapat, “Anda perlu memberi perhatian tidak hanya pada deforestasi, tetapi juga apa yang terjadi pada orang. Jender sebenarnya memberikan kacamata menarik untuk memeriksa masalah disposesi ini, yang merupakan wilayah baru yang penting.”
Ketika sebuah industri mempromosikan pekerjaan dan pencaharian petani kecil, maka perlu untuk mengingatkan akan meluasnya degradasi lingkungan, dan perspektif jender yang hilang, kata Basnett lagi. (ADV)